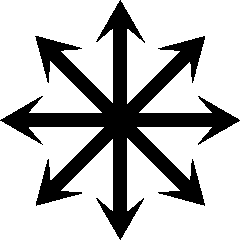Sebuah pembacaan tentang kehilangan dan kepemilikan diri
Tulisan ini lahir dari renungan tentang dua hal yang tidak bisa dihindari manusia, cinta dan kematian. Keduanya sering kita letakkan di ujung yang berlawanan, seolah cinta adalah kehidupan dan kematian adalah akhir dari segalanya. Padahal keduanya mungkin hanya dua sisi dari hal yang sama. Sama-sama menguji batas, sama-sama menuntut kita untuk menyerahkan sesuatu dari diri sendiri.Dari keduanya, aku belajar tentang arti memiliki, dan tentang bagaimana melepaskan tanpa kehilangan diri. Bahwa hidup bukan soal menolak akhir, melainkan tentang memahami bahwa apa pun yang kita pegang hanya berarti selama kita memilih untuk menggenggamnya.
Cinta dan kematian mengajarkan hal yang sama, tidak ada yang benar-benar kita punya, kecuali diri sendiri yang masih memilih untuk sadar.Maka tulisan ini bukan sekadar perenungan tentang kehilangan, tapi tentang kepemilikan. Tentang bagaimana manusia bisa berdiri di tengah keduanya tanpa tunduk pada salah satunya.
Sebuah catatan dari ruang di mana kehilangan berhenti jadi luka, dan mulai jadi kesadaran.
I. Kematian Cinta dan Kesadaran yang Tersisa
Ketika seseorang pergi, yang mati bukan hanya hubungan, tapi juga sebagian dirimu yang dulu kau ciptakan bersamanya. Kau menatap ruang yang kosong, tapi anehnya, ia masih terasa penuh. Penuh oleh kenangan, oleh harapan yang belum selesai, oleh bisikan yang terus mengulang satu kata, andai saja. Di titik itu cinta berhenti menjadi hidup, tapi belum juga berani mati. Namun dari situ juga lahir kesadaran yang keras kepala bahwa segala yang hidup pasti akan berakhir. Tidak ada janji yang abadi. Tidak ada rasa yang tak berubah. Dan dari kesadaran itu muncul gema lama, memento mori. Ingatlah, engkau akan mati.
Bagi banyak orang, kalimat itu terasa menakutkan. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah kejujuran yang paling membebaskan. Kematian menelanjangi semua yang pura-pura abadi, termasuk cinta. Dan dari situ aku mulai mengerti bahwa tidak ada apa pun yang pantas dijadikan tuan atas hidupku, bahkan rasa cintaku sendiri.
II. Mengingat Kematian dan Meruntuhkan Segala yang Suci
Dalam tradisi lama, memento mori digunakan untuk menundukkan manusia. Agar kita patuh pada Tuhan, rendah di hadapan hukum, dan takut pada akhir. Padahal kematian seharusnya menjadi pembebas terakhir. Kematian tidak memilih. Tidak menilai. Tidak menyisakan moral. Ia menelan semua yang mengaku lebih tinggi dari manusia, moralitas, agama, bahkan kenangan. Dan justru karena itu, kematian adalah cermin yang paling jujur.
Mengingat kematian bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu berarti menyadari bahwa tak ada satu pun yang lebih berkuasa atas hidup ini selain aku sendiri. Di hadapan kematian, semua nilai kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah aku yang masih berdiri, memegang kendali atas apa yang kuterima dan kutolak.
III. Mengingat Cinta yang Masih Milikku
Lalu datang memento amoris, pengingat bahwa aku pernah mencinta. Bukan untuk menyalakan kembali yang sudah padam, tapi untuk mengingat bahwa rasa itu pernah hidup di dalam aku, bukan di luar. Cinta bukan anugerah dari semesta. Bukan perintah dari moral. Ia adalah tindakan dari kehendak pribadi. Aku mencintai karena aku ingin. Aku memberi karena aku memilih untuk memberi. Dan ketika cinta berhenti memberiku kehidupan, aku juga berhak untuk berhenti. Selama cinta hidup di dalam keinginanku, ia adalah milikku. Tapi ketika cinta mulai memiliki aku, ketika ia berubah menjadi kewajiban, ketika aku terikat pada kenangan yang tak mau mati, maka cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain.
Hantu.
IV. Spook, Hantu yang Hidup di Dalam Rasa
Max Stirner menyebutnya spook, hantu-hantu ide yang hidup di kepala manusia. Segala sesuatu bisa menjadi hantu. Tuhan, moral, kemanusiaan, bahkan cinta. Mereka menuntut kesetiaan padahal tak lagi hidup. Mereka membuat kita tunduk pada sesuatu yang tak nyata, tapi terus kita beri kuasa.
Cinta, lebih dari yang lain, adalah hantu yang paling lembut. Ia datang dalam bentuk kenangan, dalam rasa bersalah, dalam bayangan yang memanggil kita untuk tetap tinggal di masa lalu. Kita menyebutnya kesetiaan, padahal sering kali itu hanya bentuk keterikatan. Kita menyebutnya tulus, padahal yang kita lakukan hanyalah menyembah bayangan seseorang yang tak lagi di sini.
Ketika cinta telah mati tapi aku masih memujanya, aku sedang berbicara pada hantu. Aku memberi nyawa pada sesuatu yang seharusnya sudah tenang. Dan di saat aku berhenti berdoa kepadanya, aku tidak kehilangan apa pun. Aku hanya membebaskan diriku sendiri.
V. Kematian, Cinta, dan Kepemilikan Diri
Baik kematian maupun cinta, pada akhirnya, berbicara tentang kepemilikan. Kematian mengingatkan bahwa tak ada yang bisa kita genggam selamanya. Cinta mengingatkan bahwa makna hanya hidup selama kita menghendakinya. Ketika keduanya bertemu dalam kesadaran penuh, lahirlah kebebasan yang sebenarnya.
Aku bisa mencinta, tapi juga bisa berhenti. Aku bisa hidup, tapi tidak takut mati. Sebab keduanya adalah bagian dariku yang tak bisa direbut.
Memento mori, memento amoris, uterque meus.
Ingatlah kematian, ingatlah cinta, keduanya milikku.
Tidak ada cinta yang suci. Tidak ada kematian yang luhur. Yang ada hanyalah aku, manusia yang mencipta makna sendiri di atas kehancuran segalanya.
VI. Aku dan Hantu yang Kini Diam
Kehilangan hanyalah pengingat bahwa tak ada yang benar-benar kita miliki selain diri sendiri.
Cinta mati, tapi rasa yang tersisa tidak perlu dibuang. Ia bisa dikembalikan ke pemiliknya, kepada aku yang masih hidup. Yang dulu menghantuiku kini menjadi cermin. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunduk. Aku tidak ingin melupakan cinta, aku hanya tidak ingin dimiliki olehnya.
Aku tidak menolak kematian, aku hanya menolak dijadikan kecil olehnya. Aku tidak ingin mengusir hantu, aku hanya ingin berhenti menyembahnya. Dan di titik itu aku benar-benar bebas. Bukan karena aku telah melupakan. Tapi karena aku telah mengakui semuanya dan menjadikannya milikku.
Publikasi ini ditulis oleh Jal